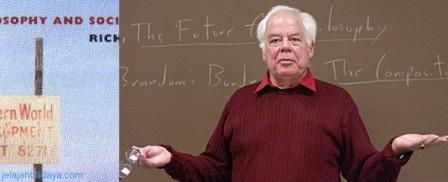 Para pemikir paham postmodern yakin bahwa narasi besar dan logosentrisme telah usang dan tidak lagi relevan. Seperti megaphone, postmodern merupakan kata yang nyaring terdengar dan memekakkan telinga. Ia mengejek juga memaki pegangan kita selama ini. Term-term seperti kebenaran, objektivitas, pengetahuan, kausalitas digantikan dengan kekuatan relativisme serta subjektivitas berdasarkan konteks ruang dan waktu, sejarah dan politik yang tentu saja beraneka rupa. Tidak heran kiranya, reportoar orang-orang seperti Nietzche, Foucault, dan Derrida atau Lyotard menjadi begitu menakutkan. Terutama bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketertiban. Begitu juga dengan Rorty.
Para pemikir paham postmodern yakin bahwa narasi besar dan logosentrisme telah usang dan tidak lagi relevan. Seperti megaphone, postmodern merupakan kata yang nyaring terdengar dan memekakkan telinga. Ia mengejek juga memaki pegangan kita selama ini. Term-term seperti kebenaran, objektivitas, pengetahuan, kausalitas digantikan dengan kekuatan relativisme serta subjektivitas berdasarkan konteks ruang dan waktu, sejarah dan politik yang tentu saja beraneka rupa. Tidak heran kiranya, reportoar orang-orang seperti Nietzche, Foucault, dan Derrida atau Lyotard menjadi begitu menakutkan. Terutama bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketertiban. Begitu juga dengan Rorty.
Richard McKay Rorty, anak pasangan James dan Winifred Rorty lahir pada tanggal 4 Oktober 1931 di New York. Rorty, meskipun diharapkan memilih bidang kerja yang “mapan”, malah terjun ke dunia pemikiran. Ia memulai karir akademiknya ketika lulus dari Universitas Chichago pada tahun 1956 dibawah bimbingan Rudolph Carnap. Setelah merampungkan disertasi bertajuk filsafat Alfred North Whitehead di Universitas Yale, Rorty berkelana menjadi dosen dan guru besar pada berbagai Universitas di penjuru Amerika. Mulai Princeton sampai Virginia dan terakhir- sampai ia wafat pada bulan Juni 2007 lalu, Rorty masih tercacatat sebagai guru besar Stanford University, salah satu universitas paling berwibawa di negeri Paman Sam.
Sejak kecil, Rorty telah terbiasa dengan keberpihakan politik yang tegas. Ibunya, adalah putri Walter Rauschenbusch, salah satu pendiri pergerakan sosial gospel Amerika, sebuah organisasi anti-Stalin yang cukup terkenal. Orang tuanya sendiri adalah penulis cum aktivis pendukung Leon Trostky, lawan politik Stalin. Tetapi uniknya, dalam perjalanan waktu, Rorty malah menaruh perhatian besar pada kelompok kiri. Rorty, seperti dikutip Ardi Amin (2006), menyarankan agar kelompok kiri sebaiknya berhenti berteori dan berfilsafat tetapi harus memikirkan bagaimana caranya berorganisasi dan mereformasi hal-hal yang khas dan unik milik mereka. Kelompok kiri juga, disarankan agar bisa berhenti memprogandakan perilaku umum untuk selalu menyamaratakan tahap kesejarahan bagi dunia global.
Lewat karya pertamanya The Lingustic Turn (1967), Rorty dengan gigih melakukan analisis terhadap kebahasaan sebagai manifestasi terhadap pengetahun manusia. Artinya, seperti komentar Franz Magnis-Suseno, apa yang kita ketahui tergantung dari bahasa yang kita pakai. Ini berimplikasi pada dua hal, pertama, bahwa keyakinan seseorang tergantung dari “kosa kata” yang dipakainya. Lantas, orang tersebut akan mencari “kosakata akhirnya”. Nah, final vocabulary itulah yang menunjukkan apa yang diyakininya. Kedua, ini yang penting, karena kosakata merupakan milik salah satu komunitas, tak ada kosakata akhir yang lebih benar daripada kosakata akhir lain.
Kalau ditarik dalam pemahaman yang lebih luas, kosakata akhir tersebut bisa berwujud pada pandangan kita terhadap berbagai macam kebenaran objektif, misalnya moralitas dan agama. Pesan Rorty yang sangat berharga yaitu, kita diharapkan menghormati identitas orang lain, sebagai identitas manusia. Tanpa tendensi. Tanpa alasan. Hanya menghormati, tanpa mencantolkan keyakinan terhadap apapun. Misalnya, ketika memilih untuk tidak menghina orang lain. Menurut Rorty, kita tidak bergargumen bahwa, “Tuhan menghendakinya”, atau “karena kita sama-sama manusia”. Disinilah kita ditantang. Bisakah kita, tanpa kebenaran objektif apapun mampu untuk tidak melukai perasaan orang lain.
Melalui buku suntingannya tersebut, Rorty meneguhkan diri sebagai filosof Amerika beraliran pragmatisme, melanjutkan tradisi yang lebih dulu dirintis oleh John Dewey, dan William James. Secara etimologis, pragmatisme bisa diartikan sebagai pengetahuan yang digunakan untuk kepentingan praktis. Tidak lagi melayani kebenaran absolut dan universal yang sifatnya objektif. Tetapi lebih condong terhadap pemenuhan subjektivitas manusia. Pemikiran itulah yang menjadi lambaran buku kedua Rorty, Philosophy and The Mirror of Nature (1979). Melalui buku tersebut Rorty kembali menegaskan sikapnya dalam menganalisis praktik sosial menggunakan pisau bedah bahasa. Proses memahami pengetahuan, bagi Rorty berarti bergulat dengan praktik-praktik sosial, dan bisa dilihat melalui interaksi serta komunikasi kebahasaan. Kerangka kerja yang seperti ini, mengantarkannya pada perjalanan lintas samudra, menemui pemikiran-pemikran Eropa daratan. Tentu saja, motif Rorty adalah untuk mendapat jawaban atas asumsi dasar filsafatnya itu.
 Disinilah lantas kita bisa menemukan Rorty dalam kapasitasnya sebagai arus pertemuan antara pragmatisme Amerika dan filsafat Barat, semisal Martin Heidegger dan Jaques Derrida. Orang mendefinisikannya sebagai neo-pragmatisme. Dalam Consequenses of Pragmatism (1982), Rorty beranggapan bahwa tidak ada sebenarnya klaim terhadap kebenaran alam transedental. Ini semata-mata perbedaan antara individu dan kominutas. Yang pribadi dan publik. Maka, dengan kata lain, Rorty mengharapkan adanya koneksi antar berbagai komunitas untuk mencapai keadilan bersama, misalnya. Dan tentu saja, ini mengatasi keyakinan satu komunitas saja. Tetapi ada pola-pola komunikasi tertentu yang pada satu titik bisa mempertemukan berbagai pandangan yang berbeda. Pencapaian kebenaran, menurut Rorty, tidak akan bisa dicapai jika kita masih terus saja berhajat untuk menyingkirkan kebenaran yang lain. Padahal, benar atau salah tidaklah ada. Yang hadir disekitar kita tidak lebih dari berwarna dan bervariasinya kosatakata akhir. Orang yang memiliki kesadaran seperti itu, Rorty mengistilahkan sebagai manusia Ironi. Rorty sendiri menolak kalau filsafatnya disebut tidak lebih dari relativistik belaka. Manusia ironi dalam bahasa Rorty, tetap memegang prinsip yang diyakininya, bahkan mungkin sampai mati-kalau ia belum menemukan pijakan lain, tetapi tetap bersedia diri untuk merayakan perbedaan.
Disinilah lantas kita bisa menemukan Rorty dalam kapasitasnya sebagai arus pertemuan antara pragmatisme Amerika dan filsafat Barat, semisal Martin Heidegger dan Jaques Derrida. Orang mendefinisikannya sebagai neo-pragmatisme. Dalam Consequenses of Pragmatism (1982), Rorty beranggapan bahwa tidak ada sebenarnya klaim terhadap kebenaran alam transedental. Ini semata-mata perbedaan antara individu dan kominutas. Yang pribadi dan publik. Maka, dengan kata lain, Rorty mengharapkan adanya koneksi antar berbagai komunitas untuk mencapai keadilan bersama, misalnya. Dan tentu saja, ini mengatasi keyakinan satu komunitas saja. Tetapi ada pola-pola komunikasi tertentu yang pada satu titik bisa mempertemukan berbagai pandangan yang berbeda. Pencapaian kebenaran, menurut Rorty, tidak akan bisa dicapai jika kita masih terus saja berhajat untuk menyingkirkan kebenaran yang lain. Padahal, benar atau salah tidaklah ada. Yang hadir disekitar kita tidak lebih dari berwarna dan bervariasinya kosatakata akhir. Orang yang memiliki kesadaran seperti itu, Rorty mengistilahkan sebagai manusia Ironi. Rorty sendiri menolak kalau filsafatnya disebut tidak lebih dari relativistik belaka. Manusia ironi dalam bahasa Rorty, tetap memegang prinsip yang diyakininya, bahkan mungkin sampai mati-kalau ia belum menemukan pijakan lain, tetapi tetap bersedia diri untuk merayakan perbedaan.
Melalui Contingency, Irony, and Solidarity (1989), Rorty berargumen bahwa lawan dari manusia ironi adalah manusia metafisik. Jenis yang terakhir ini, meyakini bahwa ada seperangkat kebenaran universal. Tugas filsafat, oleh karena itu, adalah memastikan bahwa objektivitas itu ada. Ketika itu ditemukan, maka menjadi sah untuk mengatakan bahwa kebenaran itu tunggal dan yang lain adalah salah. Ini beda dengan manusia ironi yang berpendapat bahwa proses sejarah dan keyakinan yang dimiliki, merupakan fenomena kebetulan (contingency) belaka. Dan tentu saja itu bisa berubah seriing perjalanan waktu.
Dalam konteks yang lebih luas, Rorty sangat tidak bersepakat dengan epistemologi modern. Baginya, epistemologi merupakan sebuah ruang matematis nan ajeg. Sehingga, dunia manusiawi, tersingkir karena manusia sangat berhasrat untuk lebih mementingkan metode ilmiah yang ketat dan kaku. Maka, epistemologi yang notabene merupakan bagaian dari filsafat kontemporer, menjadi terisolasi. Lebih sibuk membincang dirinya sendiri, daripada mengambil bagian dalam kontestasi sehari-hari masyarakatnya. Lebih ribet dengan urusan pengetahuan formal-kognitif, dan mengesampingkan sastra serta elemen-elemen seni lainnya, yang mungkin justru membikin manusia lebih peka.
Saya sepakat dengan pendapat Afthonul Afif (Tempo 17 Juni 2007) yang mengatakan bahwa pemikir seperti Rorty mungkin bisa dianggap sebagai pemikir paling penting yang mengubah orientasi filsafat. Filsafat, yang sejak Yunani Kuno senantiasa berorientasi “ke dalam”–ke dalam subyek reflektif yang selalu mendaku kebenaran–diserongkan ke arah filsafat yang berorientasi “ke luar”, sehingga berfilsafat tidak lagi terjadi antara subyek dan kesadarannya sendiri, tapi di antara subyek-subyek yang berusaha mencari simpul kebenaran intersubyektif melalui komunikasi intensif. Namun, pola komunikasi yang diharapkan neopragmatisme Rorty berbeda dengan pola komunikasi rasional model Habermas yang bersifat kantian dan mengutamakan komunitas ilmiah semata. Neopragmatisme Rorty menghendaki formulasi komunikasi yang dibangun di atas perubahan personal yang melibatkan sebanyak mungkin partisipasi.
Karya-Karya Utama Rorty:
- Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press, 1979.
- Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.
- Philosophy in History. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. (co-editor)
- Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers I. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Essays on Heidegger and Others: Philosophical Papers II. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth Century America. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998.
- Truth and Progress: Philosophical Papers III. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Philosophy and Social Hope. New York: Penguin, 2000.
- Against Bosses, Against Oligarchies: A Conversation with Richard Rorty. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2002.
- The Future of Religion with Gianni Vattimo; edited by Santiago Zabala. Columbia: Columbia University Press, 2005.
- Philosophy as Cultural Politics: Philosophical Papers IV. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Ahmad Ainur Rohman
Email: nunur_h at yahoo.com
kosa kata x de ke
kosa kata x de ka(contohnya)………………..
Tulisan ruwet..