Sebenarnya menarik membahas teori strukturasi Giddens secara lebih mendalam apabila kita juga bisa memahami kritik secara holistik yang dikemukakannya untuk fungsionalisme Parsons, strukturalisme Saussure – Levi-Strauss, post-strukturalisme Derrida, materialisme historis, fenomenologi, teori komunikasi Habermas, teori pilihan rasional (rational choice) sampai psikoanalisis Freud. Dengan membaca lebih jauh telaah Giddens atas berbagai pandangan teori-teori itu akan bisa memudahkan kita untuk memahami sesungguhnya teori-teori tersebut. Dalam tulisan ini sendiri, sayangnya, setidaknya sampai saat ini, tidak pernah direncanakan untuk demikian.
Kita akan memahami teori Giddens dengan setidaknya mempelajari pandangan-pandangannya untuk kedua teori yang sudah disampaikan sebelumnya, yakni fungsionalisme dan strukturalisme. Yang paling inti dalam memahami strukturasi Giddens adalah kritik kerasnya atas gejala dualisme yang melekat dalam berbagai teori khususnya dua teori di atas. Ia tidak setuju dengan dualisme struktur dan pelaku, namun ia lebih menekankan apa yang ia sebut dengan dualitas. Atas fakta struktur dan pelaku bukanlah sesuatu yang saling menegasikan atau bertentangan, tapi keduanya saling mengandaikan.
Dalam memahami pemikiran Giddens, minimal kita bisa berangkat dari dua pokok pembicaraan. Pertama, ialah pelaku (agent) dan struktur (structur), kedua ialah ruang (space) dan waktu (time).
Pelaku dan Struktur
Inilah kritik paling menonjol dalam gagasan strukturasi Giddens. Ia mengritik keras gagasan tentang hubungan keduanya yang selalu dilekati dengan dualisme sebagai pokok analisis sosiologi dalam berbagai teori. Baginya, analisis sosial semestinya menekankan pada aspek dualitas keduanya, bukan dualisme. Bahwa pelaku dan struktur berhubungan memanglah tak disangkal. Tapi bagaimana keduanya berkaitan dalam berbagai perilaku sosial, itulah yang harus dipersoalkan. Apakah pelaku dan struktur berhubungan dengan mengedepankan perbedaan (tegangan atau pertentangan) atau dualitas (timbal balik)? Ilmu sosial, menurut Giddens, selama ini dikuasai pandangan dualisme vis a vis. Ia menolak itu dan mengenalkan hubungan keduanya dalam gagasan dualitas. Pelaku dan struktur berhubungan timbal balik atau saling mengandaikan.
Pelaku adalah orang-orang yang kongkrit dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia. Struktur dalam pengertian Giddens bukanlah totalitas gejala, bukan ‘kode tersembunyi’ khas strukturalisme, cara produksi marxis, bukan sebagian dari totalitas gejala khas fungsionalisme. Struktur adalah aturan (rules) dan sumberdaya (resources) yang terbentuk (dan membentuk) dari perulangan praktik sosial. Dualitas struktur dan pelaku merupakan hasil sekaligus sarana suatu praktik sosial (Priyono, 2002). Praktik sosial yang seperti inilah yang seharusnya menjadi pokok pembahasan dalam analisis sosial. Dari pengertian seperti inilah teori stukturasi dibangun. Teori strukturasi sendiri mengandaikan sebuah proses yang terjadi dan memungkinkan terjadinya perulangan untuk membentuk perilaku sosial.
Perilaku sosial inilah yang semestinya menjadi obyek utama kajian ilmu sosial, bukan struktur atau pelaku secara terpisah. Praktik sosial itu bisa saja berbentuk penyebutan Idul Fitri dengan lebaran, fenomena mudik menjelang lebaran, memberikan zakat kepada fakir miskin, sholat id di lapangan atau masjid dan seterusnya. Dualitas yang dimaksud terletak pada struktur yang menuntun pelaku sebagai sarana (medium dan resources) dan menjadi pedoman praktik sosial di berbagai tempat. Sesuatu yang mirip ‘pedoman’ atau prinsip-prinsip ‘aturan’ itu merupakan sarana dalam melakukan proses perulangan tindakan sosial masyarakat. Giddens menyebut hal itu sebagai struktur.
Bila Durkheim memandang struktur bersifat mengekang (constraining), Giddens justru menyatakan struktur bersifat memberdayakan (enabling), dengan unsur timbal balik (dualitas) nya dengan pelaku, di dalam struktur itu memungkinkan terjadinya berbagai praktik sosial (sosial practices). Obyektivitas struktur yang terdapat dalam teori strukturasi dapat diandaikan sebagai ‘melekat’ dalam tindakan atau praktik sosial itu sendiri.
Ada tiga pokok yang biasanya terdapat dalam struktur sebagaimana dinyatakan dalam teori strukturasi Giddens (Priyono, 2002). Pertama, struktur penandaan atau signifikasi (signification -S) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana. Kedua, struktur dominasi/penguasaan (domination -D) yang menyangkut penguasaan dalam konteks politik maupun ekonomi. Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi (legitimation -L) yang berkaitan dengan peraturan normatif dalam tata hukum.
Menyebut ‘Idul Fitri sebagai lebaran’ merupakan struktur penandaan/signifikasi, penentuan hari H lebaran oleh kementerian agama merupakan struktur dominasi dalam pengertian kebijakan politik, pengaturan lalu lintas para pemudik oleh aparat polisi maupun departemen perhubungan merupakan praktik struktur legitimasi. Pada saat tertentu, gugus struktur di atas bisa saling terkait. Dalam bahasa lain, struktur dalam pengertian Giddens ini menyangkut simbol/wacana, tata ekonomi, tata politik dan tata hukum.
Dalam berbagai ‘tata’ di atas, dualitas antara pelaku dan struktur berlangsung setiap saat, dan struktur akan menjadi sarana praktik sosial. Ucapan ‘minal aizin wal faizin’ itu adalah ungkapan penandaan (signifikasi) seseorang/kelompok untuk meminta maaf kepada seseorang/kelompok yang akan bisa dipahami oleh seseorang/kelompok dalam masyarakat tertentu. Demikian pula untuk menentukan kapan berakhirnya puasa dan lebaran dimulai, setiap jam 7 atau jam 8 malam sebagian besar masyarakat menunggu hasil sidang isbath (pemerintah dan masyarakat) untuk menjadi keputusan pemerintah tentang penentuan hari lebaran. Hal yang sama juga pada saat aparat menyatakan akan menerjunkan para penembak gelap (sniper) untuk mengamankan lebaran, mengatur lalu lintas para pemudik, dan menghukum para pencopet terminal yang tertangkap saat menjalankan aksinya memanfaatkan momentum lebaran yang berdesakan.
Bila status pelaku (agent) dalam fungsionalisme Parsons atau materialisme historis Althusser adalah seperti halnya wayang di tangan dalang dan melakoni peran-peran yang sudah ditentukan, muncul pertanyaan lanjutan, apakah pelaku dalam dualitas struktur khas Giddens ini tahu dan sadar akan tindakannya? Apakah para pemudik itu tahu bahwa yang ia lakukan adalah sebuah proses ‘mudik’ atau sekedar rutinitas tak sadar pelaku bahwa setiap lebaran ia harus pulang kampung naik kereta berdesak-desakan? Giddens menyatakan bahwa setiap pelaku atas strukturnya tahu, walaupun tak selalu harus menyadari (conscious).
Di sinilah Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku (Priyono, 2002), yaitu motivasi tak sadar (unconscious motives), kesadaran praktis (practical consciousness) dan kesadaran diskursif (discursive consciousness).
Motivasi tak sadar menyangkut keinginan tak sadar pelaku yang mengarahkan pada tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Kesadaran diskursif menyangkut kemampuan pelaku untuk merefleksikan tindakannya. Sedangkan kesadaran praktis menyangkut pada kemampuan untuk melakukan tindakan yang dilengkapi dengan pengetahuan (knowledge). Melalui pengetahuan itu seterusnya pelaku melakukan tindakan sehari-hari tanpa harus mempertanyakan kembali apa yang harus dilakukan/diperankan. Kita tak lagi mempertanyakan mengapa setiap lebaran perlu mengulurkan tangan tanda meminta bersalam-salaman, perlu berkirim SMS lebaran meminta maaf, mengisi status Facebook dan Twitter kita dengan puisi-puisi lebaran dan seterusnya-dan seterusnya. Adapun aspek dinamika dari tindakan sosial ini dapat dipahami sebagai berikut, bila dahulu lebaran hanya perlu bersalaman, lalu berkembang menjadi saling berkirim kartu lebaran, saling berkirim SMS atau email, memasang banner dan spanduk di jalan-jalan sampai dengan cukup mengisi status kita di berbagai situs jejaring sosial (social networking). Dewasa ini, misalnya, para anggota dewan begitu gemar memasang spanduk dengan foto yang dikemas begitu tampan/cantik sebesar tiga perempat lebar spanduk/baliho di sudut-sudut jalan perkotaan dengan ucapan permohonan maaf lahir batin. Selain bermanfaat untuk media berlebaran, kegiatan demikian juga diandaikan bermanfaat untuk pencitraan sebagai wakil rakyat yang baik, yang terlihat peduli pada konstituennya.
Ruang dan Waktu
Ruang dan waktu adalah pokok sentral lain dalam teori strukturasi. Tidak ada tindakan perilaku sosial tanpa ruang dan waktu. Ruang dan waktu menentukan bagaimana suatu perilaku sosial terjadi. Mereka bukan semata-mata arena atau panggung suatu tindakan terjadi sebagaimana dipahami dalam teori-teori sosial sebelumnya. Mereka adalah unsur konstitutif dalam proses tindakan itu sendiri. Dengan mengadaptasi filsafat waktu Martin Heidegger, Giddens menegasikan bahwa ruang dan waktu semestinya menjadi bagian integral dalam ilmu sosial.
Unsur ruang dan waktu ini sedemikian sentralnya dalam gagasan strukturasi Giddens sehingga ia menamakan teorinya sebagai strukturasi. Tambahan –asi di dalamnya bermakna sebagai kelangsungan proses. Ada proses menjadi yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Lebaran di China tentu saja dengan lebaran di Arab Saudi, apalagi di Indonesia. Begitu pula, lebaran bagi orang dengan status sosial di ruang dan waktu yang berbeda akan menghasilkan perilaku sosial yang berbeda juga ditentukan oleh ruang dan waktu. Mereka yang berada di kota lebih mengutamakan lebaran dengan berlibur di Kebun Binatang dan yang berada di desa merayakannya dengan bersilaturrahmi. Kedua perilaku sosial yang terjadi itu dipengaruhi oleh ruang dan waktu.
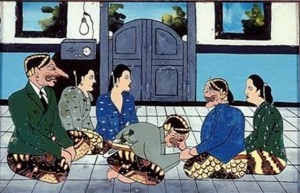 Orang yang bersalam-salaman dan meminta maaf yang terjadi di hari-hari biasa, bukan disebut sebagai proses pemfitrian sebagaimana terjadi hari raya. Pejabat yang membagi-bagi amplop dan jajanan menjelang pemilihan kepala daerah, juga bukan disebut sebagai pembagian zakat khas Idul Fitri. Giddens sungguh-sungguh menekankan bahwa ruang dan waktu bukan sekedar panggung tindakan sosial terjadi, tapi ruang dan waktu adalah unsur konstitutif dan integral dalam proses pembentukan perilaku sosial itu sendiri. Dengan kata lain, ruang-waktu, di samping menentukan makna tindakan kita di satu sisi dan menjelaskan perbedaan jenis tindakan kita di sisi lain.
Orang yang bersalam-salaman dan meminta maaf yang terjadi di hari-hari biasa, bukan disebut sebagai proses pemfitrian sebagaimana terjadi hari raya. Pejabat yang membagi-bagi amplop dan jajanan menjelang pemilihan kepala daerah, juga bukan disebut sebagai pembagian zakat khas Idul Fitri. Giddens sungguh-sungguh menekankan bahwa ruang dan waktu bukan sekedar panggung tindakan sosial terjadi, tapi ruang dan waktu adalah unsur konstitutif dan integral dalam proses pembentukan perilaku sosial itu sendiri. Dengan kata lain, ruang-waktu, di samping menentukan makna tindakan kita di satu sisi dan menjelaskan perbedaan jenis tindakan kita di sisi lain.
Koordinasi ruang-waktu, menurut Giddens, merupakan faktor utama dalam kehidupan masyarakat. Seperti dicontohkan di atas, perilaku orang bersalam-salaman bisa terjadi kapan saja dan di mana saja karena perilaku itu bukan monopoli Idul Fitri saja, namun perilaku yang sama di dalam lebaran memiliki makna yang berbeda dengan perilaku yang sama sehari-hari.
Perlu penegasan bahwa semua perilaku di sini berjalan dalam, bukan melalui, ruang dan waktu. Dalam pandangan Giddens, ruang-waktu bisa digunakan untuk membaca fenomena globalisasi, membedakan praktik sosial maupun menentukan perbedaan antara masyarakat modern dan tradisional. Itulah mengapa orang sekarang untuk beridul fitri cukup dengan menulis status di Facebook atau sekedar mengirim SMS. Hal yang sama tidak akan kita jumpai tahun 1970an, saat mana orang beridul fitri harus berjumpa dengan saudara atau kerabatnya.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudik pada era 2000an lebih didominasi oleh pemudik yang menggunakan alat transportasi umum (bus, kereta atau kapal laut) dibandingkan mudik zaman 2010 yang lebih menyukai menggunakan kendaraan pribadi, minimal motor pribadi. Gejala pembelian barang melalui sistem kredit yang semakin mudah diakses oleh siapa saja dengan persyaratan yang begitu mudah juga memberikan andil besar dalam perkembangan ini. Seseorang yang tak memiliki penghasilan tetap pun bisa mengajukan kredit kepemilikan sepeda motor atau mobil dengan mudah. Jalanan pun macet dipenuhi dengan kendaraan pribadi. Trotoar yang seharusnya diperuntukkan pejalan kaki pun kini sering dirampas oleh pengguna sepeda motor. Pejabat sering menuduh pengguna sepeda motor tidak taat aturan tanpa memahami bahwa umumnya mereka bertindak demikian karena fasilitas publik yang begitu buruk, didukung kebijakan publik yang hanya mementingkan keuntungan pejabat.
Begitulah ruang dan waktu mempengaruhi tindakan yang sama yang dilakukan pelaku dan menghasilkan praktik sosial yang berbeda. Di zaman internet ini, kini waktu dan ruang semakin lebur sebagai batas alami yang sulit ditembus. Ruang-waktu menjadi sesuatu yang bisa diatur.
***
Masih ada beberapa lagi gagasan Giddens dalam teori strukturasi ini yang menarik untuk dibicarakan, seperti soal refleksivitas-institusional yang mengakibatkan hidup seperti bahasa Giddens sebagai tunggang langgang (runaway world); hermenutika ganda yang membicarakan timbali balik antara ilmuwan sosial berikut gejala yang dianalisis; sistem abstrak yang membicarakan kehidupan manusia yang tidak bisa lepas dari sistem ahli, misalnya dengan perkembangan ledakan jumlah profesi dari hanya 5 pada masyarakat kuno (hakim, tabib, imam, guru dan serdadu) menjadi semakin tak terbatas. Namun karena keterbatasan ‘ruang –waktu’ (maksudnya kemalasan) penulis yang menyebabkan tulisan ini untuk sejenak perlu dihentikan di sini.
Selamat berlebaran mohon maaf lahir batin, dan sampai jumpa di lebaran mendatang 🙂
Lamongan, 20 September 2010
Gambar: http://i26.tinypic.com/x6bwqq.jpg
 Bagian Pertama Tulisan Ini
Bagian Pertama Tulisan Ini
Leave a Reply