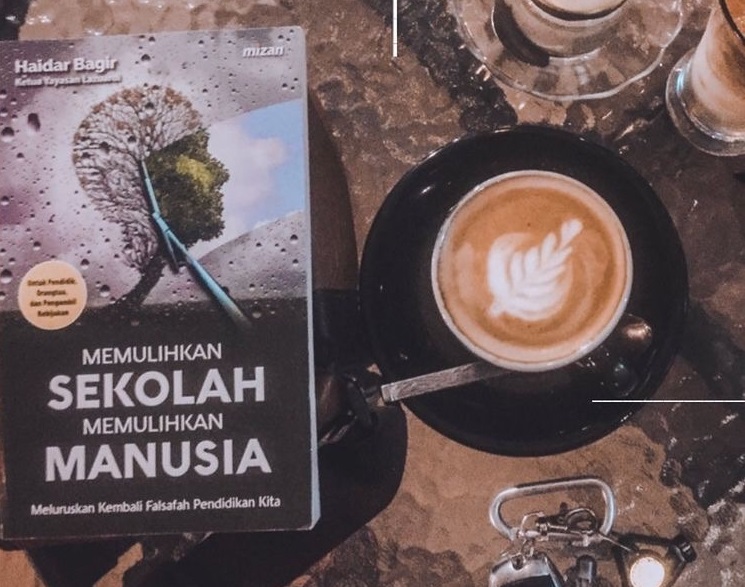
Judul: Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia
Penulis: Haidar Bagir
Penerbit: Mizan
Terbitan: 2019
Tebal: 212 halaman
ISBN: 9786024411350
Hampir setiap tahun, model pendidikan di Indonesia mengalami perubahan, entah itu dari sekadar wacana, ide-ide luar biasa yang entah bersumber dari mana, sampai kebijakan yang belum selesai pelaksanaannya dan sudah berubah lagi dengan kebijakan baru yang dicetuskan oleh penguasa. Ya, itu wajar saja, artinya sebuah negara (berkembang) sedang mengalami fase-fase pubertasnya dalam hal inovasi mengenai apa yang baik untuk dirinya.
Salah satunya ide luar biasa mengenai model pendidikan datang dari pria yang mendapat gelar master dari The Centre for Middle-Eastern Studies, Harvard University. Adalah Haidar Bagir yang juga seorang direktur utama penerbit Mizan. Pria berkelahiran 20 Februari 1957 tersebut mengemukakan beberapa ide-ide hebat mengenai pendidikan Islam, ide tersebut termaktub dalam buku setebal 212 halaman yang berjudul “Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia”
Penulis membagi buku menjadi tiga bagian utama. Bagian I menjelaskan tentang falsafah pendidikan, bagian II menjabarkan konsep dan metode pendidikan, dan bagian III membahas perihal falsafah pendidikan islam.
Bagian I, Falsafah Pendidikan
Dalam bagian satu dikupas lebih dalam yang terbagi menjadi beberapa sub bagian. Dimulai dengan “Kembali Bertanya; Apa Tujuan Sistem Pendidikan Kita?”. Haidar melihat ada absensi dalam falsafah pendidikan bangsa ini. Alih-alih terlihat seperti melahirkan warga negara-warga negara yang baik dan mampu bersaing dengan bangsa lainnya, justru berkurangnya individu yang reflektif dan berkarakter.
Akibatnya, pendidikan terus menerus dikuasai oleh aspek domain kognitif dan psikomotorik secara mubadzir seraya melupakan domain afektif dan moralitas. Parahnya lagi penggarapannya dicekokkan melalui teknik hapalan tanpa pikir (rote memorization), ketimbang menggalakkan rasa ingin tahu dan kreativitas siswa. Yang tak kurang parah, penilaian (assessment) diselenggarakan untuk mengukur hasil pencapaian akademis parsial sesaat siswa sambil mengabaikan proses dan cara-cara autentik yang mencakup karakter, serta berbagai kecerdasan dan bakat lain siswa. (hal 30).
Dalam sub bagian selanjutnya, cendikiawan muslim yang lahir di Surakarta ini mengupas bagaimana pendidikan yang memanusiakan manusia seharusnya. Bahwa manusia bukanlah artificial intelligence karena manusia memiliki jiwa dan hati. Setiap upaya dan proses pendidikan haruslah mampu melihat dan menggarap seluruh aspek potensi kemanusiaan. Hal itulah yang seharusnya dicapai oleh sistem pendidikan kita. Pendidikan yang memang membebaskan potensi sejati dari manusia itu sendiri.
Lalu sekarang, lebih penting mana mendidik anak pintar atau anak bahagia? Merangkum dari berbagai penelitian bahwa faktanya kesuksesan tak ada hubungannya sama sekali dengan kepintaran sebagaimana diukur dengan IQ. Oleh karenanya, mendorong anak untuk pintar dengan cara yang tidak bijaksana bisa menyebabkan anak kehilangan peluang karakter-karakter yang mendukung kebahagiaan.
Lebih jauh lagi, Haidar mengaitkan bagaimana hubungan 9 kecerdasan majemuk dengan IQ, EQ, dan SQ. Untuk mengetahui bakat tidak akan memberikan jaminan bahwa anak akan sukses. Bagaimanapun penting untuk melakukan penggalian dan pengembangan disertai dorongan minat yang memadai terhadap bakat itu sendiri.
Bicara kecerdasan majemuk, minat dan bakat tak lepas dari kreativitas. Dalam buku ini Haidar menjelaskan bahwa seseorang harus dalam keadaan flow yakni suasana yang nyaman dan betul-betul menikmati apa yang dilakukan untuk bisa membangkitkan kreativitasnya. Maka dalam dunia pendidikan penting membentuk atmosfer yang menyenangkan serta bebas dari ketakutan selama proses belajar-mengajar.
Karena jujur saja, mengingat kembali pada waktu jaman sekolah dulu, matematika atau yg biasa diplesetkan ‘matimatian” menjadi momok bagi sebagian peserta didik kala itu. Belum lagi dengan metode pembelajaran yang masih klasikal ditambah muka datar dan sedikit sengit khas guru pengampunya, ini seolah membuat suasana kelas menjadi tegang layaknya sebuah persidangan hukum. Tentunya itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh semua orang.
Bagian II, Konsep dan Metode Pendidikan
Masuk pada bagian dua, mengenai konsep dan metode pendidikan, Haidar banyak mengupas bagaimana dengan kurikulum pendidikan kita selama ini (sebelum Menteri Pendidikan saat ini mengumumkan keputusan untuk menghapuskan Ujian Nasional). Haidar memandang bahwa kurikulum semestinya membekali anak dengan kompetensi yang dibutuhkannya dalam kondisi nyata ketika peserta didik telah terjun dan mengambil peran di masyarakat.
Haidar nampak sepakat dengan model pembelajaran Finlandia, di mana orientasi terhadap proses lebih penting ketimbang hasil yang mengutamakan kenyamanan belajar siswa. Konsepnya tidak mengenal Pekerjaan Rumah (PR) dan istirahat diperbanyak. Menurut Haidar, sekolah hakikatnya bukanlah tempat berhasil melainkan tempat “gagal”. Artinya sekolah bisa menjadi tempat yang asyik bagi siswa dalam memfasilitasi anak-anak mengembangkan keingintahuannya, trial and error atas percobaannya, hingga kelak berhasil dalam arti sesungguhnya.
Sudah waktunya kita mengingatkan kembali pentingnya menjadikan hal-hal lain di luar sains dan matematika sebagai kriteria keberhasilan pendidikan di negeri kita. (Hal 159).
Bisa dibayangkan betapa bahagianya ketika sekolah siswa tidak terbebani dengan mengejar peringkat. Belajar dimaknai sebagai upaya untuk mencoba suatu hal yang baru dan menuangkan segala imajinasi dengan dukungan sekolah. Mungkin lagu “pagiku cerahku, matahari bersinar” akan terus dinyanyikan dalam perjalanan menuju sekolah.
Di akhir bagian dua, Haidar mengupas tentang ujian nasional dengan pertanyaan apakah Ujian Nasional efektif membuat siswa bekerja keras atau justru memunculkan celah manipulasi nilai sekaligus memberikan pengajaran terselubung kemerosotan karakter.
Bagian III, Falsafah Pendidikan Islam
Di bagian terakhir ini Haidar mengupas falsafah pendidikan Islam. Di mana di dalamnya dibahas bagaimana perspektif Islam tentang pendidikan. Perbedaan Tarbiyah dan Ta’dib, yangmana Ta’dib (pengadaban) menjadi tujuan puncak setiap proses pendidikan.
Menurut Haidar, mengajarkan agama dengan benar adalah dengan mengajarkan akhlak. Ia menganggap bahwa akhlak adalah puncak agama dan bukan sekadar pelajaran tata cara beribadah legal-formalitas dan bersifat hafalan, yang kosong dari makna batinnya sebagai pengembangan akhlak mulia. Layaknya sebuah bekal makanan nilai penting adalah isinya, bukan wadahnya. Meskipun tupperware yang harganya berjuta-juta tetapi isinya hanya nasi goreng bekas malam kemarin yg di hangatkan, akan kalah dengan rantang yang isinya sayur lodeh lengkap dengan sambal beserta tempe hangatnya.
Haidar juga mengkhawatirkan mengenai pelajaran biografi (sirah) Nabi Muhammad. Apa yang dikhawatirkan adalah apabila anak-anak sekolah di benaknya terpikir bahwa sebagian besar masa hidup Nabi itu berperang. Padahal menurut penelitian jika dijumlahkan seluruh perang Nabi hanya memakan waktu total 800 hari. Penelitian lain yang tak memasukkan hari-hari persiapan, ekspedisi yang tak berujung pada peperangan, mendapati totalnya hanya 80 hari.
Jika melihat jejak Nabi Muhammad sebagai Nabi selama 23 tahun, artinya hanya 10% harinya yang terpakai untuk peperangan. Apalagi kalau mengambil data yang 80 hari artinya hanya 1%. Sisanya yang 90-99% adalah digunakan untuk mengajarkan akhlak mulia dan memberikan teladan tentang hamba Allah yang tugasnya menyebarkan rahmat bagi semesta alam.
Pada akhirnya, Haidar menutup Bagian III ini dengan orientasi akhlak (Budi Pekerti atau Karakter) dalam pendidikan agama. Menurutnya kelemahan pendidikan agama di bangku sekolah adalah masih terpusat pada hal-hal yang bersifat simbolis, ritualis, dan legal-formal. Padahal pendidikan yang baik harus menggarap tiga ranah kemanusiaan, yakni ranah kognitif (intelektual), ranah afektif (emosional), dan ranah psikomotorik. Kenyataannya, banyak di antara penganut agama gemar mendengarkan ceramah, berdiskusi, berdebat berbagai isu keagamaan namun tak ada wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Berapa banyak orang sadar, betapa besar keinginan untuk berbuat baik, tetapi sedikit dan sulit terwujud dalam kenyataan. Artinya ada ranah psikomotorik yang kurang terjamah. Ranah psikomotorik ini meliputi kejujuran, kerja keras, professionalisme, kesopanan, dan filantropi sosial dalam pengembangan disiplin. Dengan demikian penyusunan materi pelajaran agama di sekolah haruslah mengarah pada penanaman akhlak. Karena sesungguhnya akhlak ini adalah perwujudan dari Rukun Ihsan.
Leave a Reply