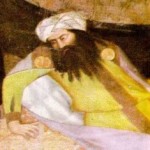
ABU Ya‘la al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd (1126-1198), atau yang lebih terkenal dengan sebutan Ibn Rusyd atau Averroes, adalah filosof Muslim Barat terbesar di abad pertengahan. Dia adalah pendiri pikiran merdeka sehingga memiliki pengaruh yang sangat tinggi di Eropa. Michael Angelo meletakkan patung khayalinya di atas atap gereja Syktien di Vatikan karena ia dipandang sebagai filosof free thinker. Dante dalam Divine Comedia-nya menyebutnya “Sang Komentator” karena dia dianggap sebagai komentator terbesar atas karya-karya Aristoteles.[1]
Biografi Singkat
Secara resmi, Ibn Rusyd memang diminta oleh Amir Abu Ya‘la Ya’qub Yusuf untuk menulis komentar atas berbagai karya Aristoteles, di mana untuk setiap buku dia membuat tiga kategori komentar: ringkasan (jami’), komentar singkat (talkhis) dan komentar detail (sharh atau tafsir). Yang terakhir disiapkan untuk mahasiswa tingkat tinggi.[2] Akan tetapi, untuk jangka waktu yang sangat lama, di dunia Muslim, Ibn Rusyd tidak dikenal karena komentar-komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles, tapi karena Tahafut al-Tahafut-nya yang ditulisnya sebagai bantahan terhadap terhadap buku al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah. Komentar-komentarnya banyak berada di dunia Yahudi dan Kristen sehingga kebanyakan komentar-komentarnya tidak lagi ditemukan dalam bahasa Arab, tapi sudah dalam bentuk terjemahan bahasa Hebrew atau Latin.
Memang, Ibn Rusyd merupakang komentator besar karya-karya Aristoteles, namun perhatian intelektualnya yang vital dalam konteks pemikiran filsafat Islam diabaikan, kita telah berbuat tidak adil terhadapnya. Sekalipun bersikap sebaliknya juga sama tidak adilnya. Akan tetapi bagaimanapun juga, untuk memperoleh suatu pemahaman yang benar tentang pemikiran filosofis dan teologis Ibn Rusyd, sumber yang paling penting tentu saja Tahafut al-Tahafut.
Ia lahir di Kota Cordova, Ibu Kota Andalusia.Kakeknya adalah seorang ahli fiqh dan ilmu hukum terkenal. Di samping menjabat sebagai imam besar di Masjid Jami’ Cordova, ia juga diangkat menjadi hakim agungn (qadi al-jama’ah). Setelah meninggal, jabatan hakim agung ini diteruskan oleh puteranya, ayah Ibn Rusyd.
Tampak di sini bahwa Ibn Rusyd terlahir dari keluarga ahli-ahli fiqh dan hakim-hakim. Tidak mengherankan jika salah satu karyanya yang sangat terkenal, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, merupakan karyanya dalam bidang fiqh. Buku ini merupakan suatu studi perbandingan hukum Islam, di mana di dalamnya diuraikan pendapat Ibn Rusyd dengan mengemukakan pendapat-pendapat imam-imam fiqh.
Dia juga sebagai seorang dokter dan astronomer. Tapi, posisi ini kurang terkenal dibanding dengan reputasinya sebagai filosof. Dia dianggap sebagai salah satu dokter terbesar di zamannya. Menurut Sarton[3] dia adalah orang pertama yang menerangkan fungsi retina dan orang pertama yang menjelaskan bahwa serangan cacar pertama akan membuat kekebalan berikutnya pada orang yang bersangkutan.
Agama dan Filsafat: Sebuah Upaya Rekonsiliasi Filosofis
Doktrin utama filsafat Ibn Rusyd yang membuatnya dicap sebagai murtad berkaitan dengan keabadian dunia, sifat pengetahuan Tuhan dan kekekalan jiwa manusia dan kebangkitannya.[4] Membaca sekilas tentang Ibn Rusyd memang bisa memberi kesan bahwa dia murtad dalam hubungannya dengan masalah-masalah tersebut, tapi penelaahan yang serius akan membuat orang sadar bahwa dia sama sekali tidak menolak ajaran Islam. Dia hanya menginterpretasikannya dan menjelaskannya dengan caranya sehingga bisa sesuai dengan filsafat.
Terhadap doktrin keabadian dunia, dia tidak menolak prinsi penciptaan (creation), tapi hanya menawarkan satu penjelasan yang berbeda dari penjelasan para teolog. Ibn Rusyd memang mengakui bahwa dunia itu abadi, tapi pada saat yang sama membuat pembedaan yang sangat penting antara keabadian Tuhan dengan keabadian dunia. Ada dua macam keabadian: keabadian dengan sebab dan keabadian tanpa sebab. Dunia bersifat abadi karena adanya satu agen kreatif yang membuatnya abadi. Sementara, Tuhan abadi tanpa sebab. Lebih dulunya Tuhan atas manusia tidak terkait dengan waktu. Keberadaan Tuhan tidak ada kaitannya dengan waktu karena Dia ada dalam keabadian yang tak bisa dihitung dengan skala waktu. Lebih dulunya Tuhan atas dunia ada dalam keberadaan-Nya sebagai sebab yang darinya muncul semua keabadian.[5]
Bagi Ibn Rusyd, tidak ada creatio ex nihilio, tapi penciptaan adalah proses perubahan dari waktu ke waktu. Menurut pandangan ini, kekuatan kreatif terus-menerus bekerja dalam dunia, menggerakannya dan menjaganya. Adalah mudah untuk menyatukan pandangan ini dengan konsep evolusi.
Penting juga untuk dinyatakan di sini tentang sanggahan al-Ghazali tentang hukum kausalitas. Al-Ghazali tidak menerima hukum kausalitas dengan dua alasan utama. Pertama, hukum kausalitas bertentangan dengan kekuasaan mutlak Tuhan atas dunia. Korelasi yang dinyatakan sebagai hukum sebab-akibat tidak ditopang oleh pengalaman dan logika. Pengalaman indra hanya memberi pengetahuan tentang rentetan kejadian dan tidak ada alasan apapun untuk mengatakan bahwa rangkaian temporal suatu kejadian menunjukkan proses sebab-akibat.[6] Tidak ada sebab-akibat karena semuanya terjadi berdasarkan takdir Tuhan. Kalau tuhan menghendaki, maka runtutan kejadian yang selama ini dianggap sebagai sebab-akibat bisa tidak terjadi, sebagaimana dalam kejadian-kejadian luar biasa, atau yang biasa disebut dengan mukjizat.
Ibn Rusyd menyanggah tuduhan al-Ghazali tersebut dengan menyatakan bahwa tujuan al-Ghazali untuk memutlakkan kekuasaan Tuhan dengan cara menghapus hukum sebab-akibat justru kontraproduktif. Penolakan hukum sebab-akibat akan menghancurkan seluruh basis untuk mengarahkan seluruh proses kejadian di alam kepada tuhan. Al-Ghazali secara tidak sadar telah menghancurkan satu-satunya dasar logis di atas mana kekuasaan Tuhan terhadap alam bersandar.
Penanggalan itu sama-sama membahayakan filsafat, ilmu dan juga teologi.Jika segala sesuatu tejadi secara kebetulan dan tergantung pada keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga, maka tidak ada pola rasional yang dapat kita amati dalam ciptaan. Ini juga berarti menghancurkan konsep Tuhan sebagai pencipta alam dan pengatur yang maha bijaksana. Dari sudut ini, maka tidak ada jalan lagi untuk membuktikan eksistensi Tuhan dari sudut pandang keindahan dan keteraturan yang kita saksikan di dunia ini atau untuk menolak argumen kaum materialis yang menunjuk semua kejadian di dunia ini kepada kekuatan-kekuatan kebetulan yang buta. Tesis ini jelas membahayakan, baik bagi filsafat maupun al-Qur’an yang telah menyatakan dengan tegas dunia sebagai sebagai karya Tuhan yang sempurna.[7]
Sementara yang berhubungan dengan pengetahuan Tuhan, Ibn Rusyd tampak mengikuti pandangan para filosof bahwa Tuhan hanya mengetahui keberadaanya sendiri. Bagi filosof, pandangan ini merupakan keniscayaan agar Tuhan tetap terjaga keesaan-Nya karena jika Dia mengetahui keragaman segala sesuatu, Dia berarti juga memiliki keragaman dalam diri-Nya. Jalan pikiran ini akhirnya meletakkan Tuhan untuk semata-mata berada dalam diri-Nya sendiri dan tidak ada yang lain.
Sebagai seorang Aristotelian sejati, Ibn Rusyd mengikuti pandangan “gurunya” tersebut. Arsitoteles berpendapat bahwa sat-satunya obyek yang cocok bagi pengetahuan Tuhan adalah esensi Ilahi sendiri. Pendapat ini dimunculkan karena hasrat untuk menyucikan (tanzih) Tuhan dari sifat cela dan kesemantaraan yang menjadi konsekuensi dari pengetahuan tentang hal-hal yang partikular. Ibn Rusyd mengikuti argumen ini dengan berusaha “menyelamatkan” Tuhan dari sifat ketidaktahuan sebagai yang secara implisit terkandung dalam pandangan Aristoteles tersebut. Ibn Rusyd menyatakan bahwa dalam mengetahui Dirinya sendiri, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada bedasarkan Wujud itu yang merupakan sebab bagi eksistensi segala sesuatu. Dengan begitu, Wujud Pertama mengetahui segala wujud partikular melalui Dirinya sendiri.[8]
Filsafat Ibn Rusyd memiliki elastisitas yang tinggi. Ia menyatakan bahwa Tuhan dalam mengetahui esensi diri-Nya sendiri mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia karena pada akhirnya Dia adalah sumber dan landasan utama dari segala sesuatu. Pengetahuan Tuhan tidak seperti pengetahuan manusia. Jadi, kalau al-Ghazali menyerang para filosof dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengakui pengetahuan Tuhan terhadap yang partikuler, bagi Ibn Rusyd, al-Ghazali tidak memahami filsafat karena yang tidak diakui oleh para filosof adalah penyamaan pengetahuan Tuhan dengan manusia.
–Lanjutan tulisan ini bisa dibaca di buku 7 Filsuf Muslim Pembuka Pintu Gerbang Filsafat Barat Modern (LKiS, 2003).
BACAAN
Affandi, Khozin. Diktat Filsafat Ilmu. Surabaya: Penerbitan IAIN Sunan Ampel, 1998.
Affifi, A.E.. Filsafat Mistis Ibnu `Arabi. Ter. Sjahrir Mawi dan Nandi Rahman. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1995.
Ahmad, Manzhoor. “Metafisika Persia dan Iqbal.” M. Iqbal. Metafisika Persia: Suatu Sumbangan untuk Sejarah Filsafat Islam. Ter. Joebaar Ayoeb. Bandung: Mizan. 1995.
Ahmad, Zainal Abidin. Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes) Filosuf Islam Terbesar di Barat. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Al-Ahwani, Ahmad Fuad. Al-Kindi Failasuf al-Arab. Mesir: Al-Matabi al-Hay’at al-Misriyah, 1985.
Al-Ghazâlî. al-Munqidh min al-Dalâl wa ma’a Kimiya al-Sa’âdah wa al-Qawâ’id al-Ashrata wa al-Adab fi al-Dîn. Libanon: al-Maktabah al-Sya’bîyah, tt.
Ali, Syed Amir. The Spirit of Islam: A History of Evolution and Ideals of Islam with a Life of the Prophet. Delhi: Low Price Publication, 1995.
Al-Razi. Rasa’il Falsafiyah. ed. Lajnah al-Turas al-Araby. Bairut: Dar al-Alaq al-Jadidah, 1982.
Atiyeh, George N. Al-Kindi: Tokoh Filosof Muslim. ter. Kasidjo Djojosoewarno. Bandung: Pustaka Salman, 1983.
Azhim, Ali Abdul. Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Perspektif al-Qur’ân, ter. Khalilillah Ahmas Hakim. Bandung: CV. Rosda, 1989.
Bakar, Osman. Hierarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu Menurut Al-farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazi. ter. Purwanto. Bandung: Mizan, 1997.
Beck, H.L. & N.J.G. Kaptein. Pandangan Barat terhadap Literatur, Hukum, Filosof, Teologi dan Mistik Tradisi Islam. Jakarta: INIS, 1988.
Bertens, K. Ringkasan Sejarah Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
Brockelmann, Carl. History of the Islamic Peoples. London: Routledge &Paul Kegan Limited. 1949.
Cornman, James W “Epistemologi”, Encyclopeadia Americana. Robert S. Anderson at. al. (eds.). Vol. 10. Danbury, Connecticut: Americana Corporation, 1978.
De Boer, T.J.. The History of Philosophy in Islam. trans. Edward R. Jones B.D.. New York: Dover Publication, Inc., t.t..
Sutrisno, Mudji & F. Budi Hardiman. Para Filsuf Penentu Gerak Zaman. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
Ewing, A.C.. The Fundamental Question of Philosophy. New York: Collier Books, 1962.
Fakhry, Majid. A History of Islamic Philosophy. New York: Columbia University Press, 1983.
Fakhry, Majid. Sejarah Filsafat Islam. ter. Drs. R. Mulyadi Kartanegara. Jakarta: Pustaka Jaya. 1987.
Fradkin, Hillel. “The Political Thought of Ibn Tufayl.” The Political Aspect of Islamic Philosophy. Charles E. Butterworth (ed.). Cambridge: Harvard University Press, 1992.
Gibb, H.A.R.. Mohammedanism. Oxford: Oxford University Press. 1952.
Hadi, P. Hardono. Epistemologi: Filsafat Pengetahuan. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
Hadiwiyono, Harun. Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
Haque, M. Atiqul. Wajah Peradaban: Menelusuri Jejak Pribadi-Pribadi Besar Islam. terj. Budi Rahmat et. al.. Bandung: Zaman, 1998.
Hayy ibn Yaqzan li ibn Sina wa Ibn Tufayl wa Suhrawardy. Ahmad Amin (ed.). Kairo: Dar al-Ma’arif, 1966.
Hidayat, Komaruddin. Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika. Jakarta: Paramadina, 1996.
Hitti, Philip K. History of Arab. London: Macmillan Ltd., 1973.
Iverach, James. “Epistemologi”. Encyclopaedia of Religion and Ethich. James Hastings (ed.). Vol. 5. New York: Charles Scribner’s Sons, 1995.
Jahja, Zurkani. Teologi al-Ghazâlî: Pendekatan Metodologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Jurnal Filsafat. 28. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Juli. 1997.
Kattsoff, Louis O.. Pengantar Filsafat. terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995.
Koesnoe, Moh. Pengantar ke Arah Filsafat Hukum: Suatu Catatan Kuliah. Surabaya: UBHARA Press, 1997.
Lewis, Bernard. The Arabs in History. New York: Harper Torchbooks. 1967.
Madjid, Nurcholish (ed.). Khazanah Intelektual Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1884.
Madkur, Ibrahim. Fi al-Falsafah al-Islamiyah: Manhaj wa Tadbikuh, I. Mesir: Dal al-Ma`arif, 1976.
Madkour, Ibrahim. Filsafat Islam: Metode dan Penerapannya I. ter. Yudian Wahyudi Asmin dan Ahmad Hakim Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Mustansyir, Rizal. “Aliran-Aliran Metafisika (Studi Kritis Filsafat Ilmu).” Jurnal Filsafat. 28. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Juli. 1997.
Mustafa, H.A.. Filsafat Islam. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
Nafis, Muhammad Wahyuni (ed.). Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam. Jakarta: Paramadina, 1996.
Nasr, Seyyed Hossein. Science and Civilizatiob in Islam. New York: New American Library, 1970.
Nasution, Harun. Filsafat dan Mistisisme dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1973.
Nasution, Hasyimsyah. Filsafat Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
Noer, Kautsar Azhari. Ibn al-`Arabi: Wahdat al-Wujud dalam Perdebatan. Jakarta: Paramadina. 1995.
Poerwantana et. al.. Seluk Beluk Filsafat Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
Pradja, Juhaja S. Aliran-Aliran Filsafat dari Rasionalisme Hingga Sekulerisme. Bandung: Alva Gracia, 1987.
Qadir, C.A.. Philosophy and Science in the Islamic World. London: Routledge. 1991.
Rahman, Fazlur. Islam. Ter. Achsin Mohammad. Bandung: Pustaka. 1994.
Rosenthal, E.E.. “Avicenna’s Influence on Jewish Thought.” G.M. Wickens (ed.). Avicenna: Scientist and Philosopher. London: Routledge, 1952.
Russel, Bertrand. History of Western Philosophy. London: Routledge, 1991.
Sarton, G. Introduction of the History of Science. vol. II. Baltimore, 1931.
Shaikh, Saeed. Studies in Muslim Philosophy. Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.
Siddiqi, Bakhtyar Husain. “Ibnu Tufail.” A History of Muslim Philosophy. M.M. Sharif (ed.). vol. I. Delhi: Low Price Publication, 1995.
Spinoza, Benedict de. “Ethics.” Ter. W.H. White. Great Books of the Western World. Chicago: Encyclopaedia Britanica, Inc.. 1986.
Syarif, M.M.. Para Filosof Muslim. ter. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan, 1993.
von Grunebaum, G.E.. Classical Islam: A History 600-1258. trans. Kathrine Watson. London: George Allen and Unwin Ltd., 1970.
Watt, W. Montgomery. Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey. Edinburg: Edinburg University Press, 1992
M Zainul Hamdi
Sekilas Ahmad Zainul Hamdi
Ia lahir di Lamongan, 18 Mei 1972. Demonstrasi dan menjadi tokoh utama demonstran penentang Orde Baru (di Malang) adalah pekerjaan utama dan profesi ketika menjadi mahasiswa di S-1 IAIN Sunan Ampel Malang, sampai ahirnya bakatnya membaca, menulis dan mengajar ditemukan serta dipupuk di S-2 IAIN Sunan Ampel Surabaya (Konsentrasi Pemikiran Islam). Sekarang menjadi tenaga pengajar di STAIN Ponorogo untuk mata kuliah Filsafat Islam dan Perkembangan Pemikiran dalam Islam. Karya tulis yang sudah dipublikasikan adalah Tak Bergeming di Bawah Tatapan Tuhan (Danar Wijaya, 2000), 7 Filsuf Muslim Pembuka Pintu Gerbang Filsafat Barat Modern (LKIS, 2003).
[1] Zainal Abidin Ahmad, Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes) Filosuf Islam Terbesar di Barat (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 31.
[2] Carl Brockelman, History of the Islamic People (London: Routledge & Kegan Paul Limited, 1949), 210.
[3] G. Sarton, “Introduction of the History of Science, vol. II (Baltimore, 1931), 356.
[4] Ibid., 210.
[5] Shaikh, Studies, 173.
[6] Alasan al-Ghazali untuk menolak hukum sebab-akibat, terutama yang kedua, juga disuarakan oleh filosof empirisis-skeptis di era modern, David Hume, dengan logika yang sama. Sejauh pengetahuan hanya disandarkan pada persepsi inderawi, maka hukum sebab-akibat harus ditolak karena hukum tersebut semata-mata diturunkan dari persepsi inderawi. Sementara pandangan mata tidak memberi informasi apa pun kecuali rentetan kejadian. Lalu, dari mana hukum sebab-akibat tersebut disimpulkan? Tentang argumentasi Hume ini, lihat Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2 (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 54-55.
[7] Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam, ter. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: Pustaka Jaya, 1987), 393-394.
ibnu rusyd memang pemikir rasionalis Islam dan sebagai bapak pendiri mazhab rasionalis, namun dalam sejarah pemikiran Islam, bahwa setiap persoalan yang dihadapi ummat itu berbeda sama sekali dari masa ke masa. jika pada awal islam dimana terjadi pencerahan dalam pemikiran ummat itu dikarenakan karena ghriiah intelektual yang ada pada waktu itu. namun lambat laun permasalahan tergeser menjadi paradigma ekonomi kapitalistik. saya boleh mengatakan apapun saat ini yang terjadi dan menggejala kita harus mellihat dari kacamata ekonomi kapitalis. marx memang pengaruhnya sangat besar terhadap pemikiran manusia dari waktu ke waktu. maka dari itu hendaknya permasalahan Islam saat ini tidak melulu pada teoritik tapi aplikatif. kembali ke awal bahwa upaya ibnu rusyd itu adalah “ihya’ din”. berbeda dg al ghazali yang menghidupkan ilmu agama dari sisi teologis tapi ibnu rusyd dari sisi rasionalitas dalam beragama. ia mendukung filsafat untuk dijadikan pijakan total dalam mengarungli lkehidupan. sebenarnya wahy u dan filsaft tidaklah bertentagan.
Sy msih penasaran tentang biografi ibnu rusdi : ”tolong pa di lengkapi lagi pemikiran ibnu rusdi yang menyangkut filsafatnya..!trmks pak.